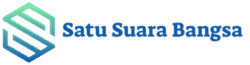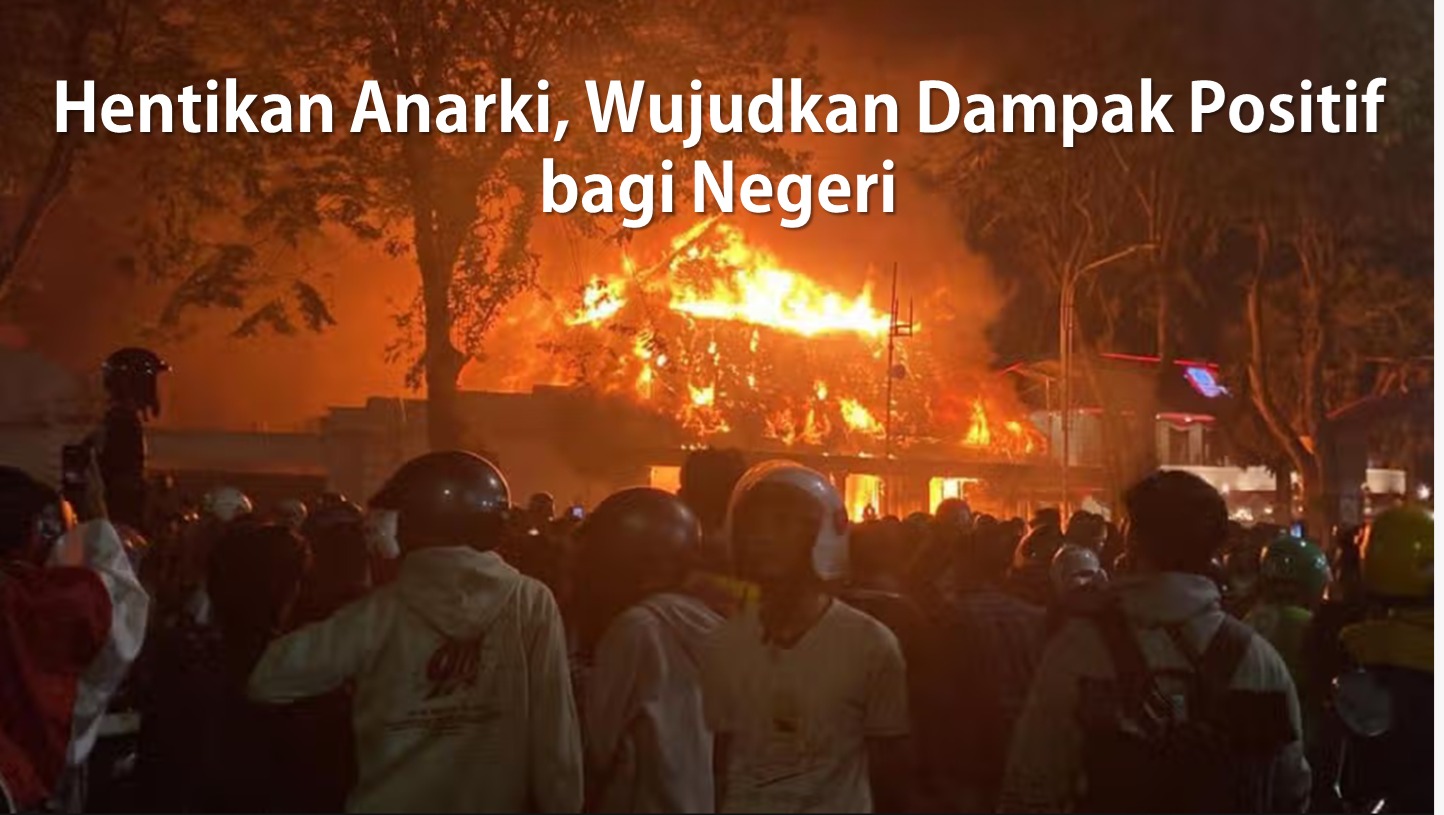Kenaikan harga beras hingga 5% dalam beberapa minggu terakhir bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal penting bahwa sistem pangan nasional masih belum cukup kokoh dalam menghadapi tekanan. Saat harga eceran beras menembus angka Rp14.784 per kilogram, masyarakat langsung merasakan dampaknya, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok. Beras bukan barang mewah, melainkan kebutuhan harian yang tidak bisa digantikan. Karena itu, perubahan kecil pada harga membawa dampak besar pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Lonjakan harga ini juga menjadi cermin rapuhnya rantai pasok dan distribusi pangan kita, serta menguatkan argumen bahwa Indonesia tidak bisa terus menggantungkan kebutuhan pangannya pada impor atau mekanisme pasar global yang tidak stabil.
Ketergantungan pada impor dan lemahnya koordinasi distribusi pangan domestik menciptakan ketergantungan jangka panjang yang berisiko tinggi. Ketika pasokan luar negeri terganggu karena faktor cuaca, geopolitik, atau krisis global, harga langsung terdorong naik tanpa bisa dikendalikan secara cepat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat menjadi korban utama dari sistem yang rapuh. Padahal Indonesia memiliki semua prasyarat untuk mandiri secara pangan: lahan subur, iklim tropis yang mendukung pertanian sepanjang tahun, dan tenaga kerja tani yang besar. Masalahnya bukan pada potensi, melainkan pada sistem yang belum terkelola optimal, dari produksi hingga distribusi. Kemandirian pangan hanya bisa terwujud jika negara berpihak penuh pada penguatan sektor pertanian domestik secara berkelanjutan dan menyeluruh.
Untuk merespons tantangan ini, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai langkah konkret telah dilakukan guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan beras di pasar. Melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sebanyak 1,3 juta ton beras disalurkan demi menekan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, sebanyak 18 juta keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan langsung berupa 20 kilogram beras setiap bulan, sebagai upaya menjaga daya beli dan konsumsi pangan rumah tangga miskin. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, intervensi ini juga bertujuan mencegah spekulasi harga dan menekan dominasi pasar yang bisa merugikan konsumen dalam jangka panjang.
Namun kebijakan yang adil tidak hanya menyasar konsumen, tapi juga harus melindungi produsen—yakni para petani. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah agar petani tidak dirugikan saat harga pasar jatuh. Ini penting sebagai jaring pengaman ekonomi bagi petani, sekaligus mendorong mereka tetap semangat berproduksi. Tak cukup sampai di situ, pemerintah juga memperkuat sisi hulu melalui pembangunan Food Estate dan penerapan pertanian presisi berbasis teknologi digital. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi lahan, dan daya saing hasil pertanian nasional. Dengan dukungan teknologi, pelatihan, dan akses terhadap permodalan serta pasar, petani Indonesia dapat naik kelas dan menjadi aktor utama dalam ekosistem pangan nasional.
Ketahanan pangan sejatinya adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan komitmen kolektif dari negara dan seluruh elemen masyarakat. Negara harus terus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memberdayakan. Masyarakat perlu mendukung dan terlibat aktif, baik sebagai konsumen cerdas maupun mitra pembangunan. Jika seluruh rantai pangan dari hulu ke hilir diperkuat secara konsisten, maka Indonesia akan memiliki sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Di situlah titik temu antara kesejahteraan petani, kestabilan harga, dan kedaulatan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan sekadar mimpi, melainkan keniscayaan yang bisa dicapai dengan kerja nyata dan kolaborasi bersama demi masa depan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.